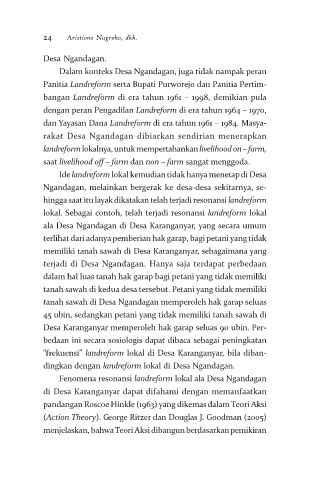Page 37 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 37
24 Aristiono Nugroho, dkk.
Desa Ngandagan.
Dalam konteks Desa Ngandagan, juga tidak nampak peran
Panitia Landreform serta Bupati Purworejo dan Panitia Pertim-
bangan Landreform di era tahun 1961 – 1998, demikian pula
dengan peran Pengadilan Landreform di era tahun 1964 – 1970,
dan Yayasan Dana Landreform di era tahun 1961 – 1984. Masya-
rakat Desa Ngandagan dibiarkan sendirian menerapkan
landreform lokalnya, untuk mempertahankan livelihood on – farm,
saat livelihood off – farm dan non – farm sangat menggoda.
Ide landreform lokal kemudian tidak hanya menetap di Desa
Ngandagan, melainkan bergerak ke desa-desa sekitarnya, se-
hingga saat itu layak dikatakan telah terjadi resonansi landreform
lokal. Sebagai contoh, telah terjadi resonansi landreform lokal
ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, yang secara umum
terlihat dari adanya pemberian hak garap, bagi petani yang tidak
memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, sebagaimana yang
terjadi di Desa Ngandagan. Hanya saja terdapat perbedaan
dalam hal luas tanah hak garap bagi petani yang tidak memiliki
tanah sawah di kedua desa tersebut. Petani yang tidak memiliki
tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap seluas
45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di
Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin. Per-
bedaan ini secara sosiologis dapat dibaca sebagai peningkatan
“frekuensi” landreform lokal di Desa Karanganyar, bila diban-
dingkan dengan landreform lokal di Desa Ngandagan.
Fenomena resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan
di Desa Karanganyar dapat difahami dengan memanfaatkan
pandangan Roscoe Hinkle (1963) yang dikemas dalam Teori Aksi
(Action Theory). George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2005)
menjelaskan, bahwa Teori Aksi dibangun berdasarkan pemikiran