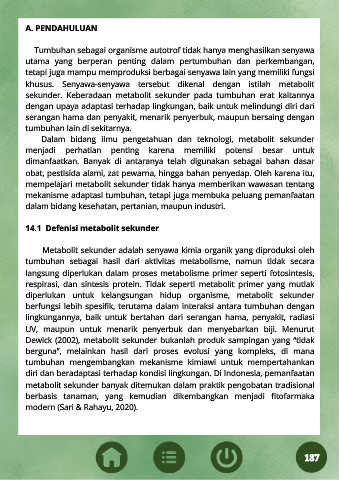Page 199 - Buku Digital Interaktif Dilengkapi AR Dan VR Fisiologi Tumbuhan
P. 199
A. PENDAHULUAN
Tumbuhan sebagai organisme autotrof tidak hanya menghasilkan senyawa
utama yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan,
tetapi juga mampu memproduksi berbagai senyawa lain yang memiliki fungsi
khusus. Senyawa-senyawa tersebut dikenal dengan istilah metabolit
sekunder. Keberadaan metabolit sekunder pada tumbuhan erat kaitannya
dengan upaya adaptasi terhadap lingkungan, baik untuk melindungi diri dari
serangan hama dan penyakit, menarik penyerbuk, maupun bersaing dengan
tumbuhan lain di sekitarnya.
Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, metabolit sekunder
menjadi perhatian penting karena memiliki potensi besar untuk
dimanfaatkan. Banyak di antaranya telah digunakan sebagai bahan dasar
obat, pestisida alami, zat pewarna, hingga bahan penyedap. Oleh karena itu,
mempelajari metabolit sekunder tidak hanya memberikan wawasan tentang
mekanisme adaptasi tumbuhan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan
dalam bidang kesehatan, pertanian, maupun industri.
14.1 Defenisi metabolit sekunder
Metabolit sekunder adalah senyawa kimia organik yang diproduksi oleh
tumbuhan sebagai hasil dari aktivitas metabolisme, namun tidak secara
langsung diperlukan dalam proses metabolisme primer seperti fotosintesis,
respirasi, dan sintesis protein. Tidak seperti metabolit primer yang mutlak
diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme, metabolit sekunder
berfungsi lebih spesifik, terutama dalam interaksi antara tumbuhan dengan
lingkungannya, baik untuk bertahan dari serangan hama, penyakit, radiasi
UV, maupun untuk menarik penyerbuk dan menyebarkan biji. Menurut
Dewick (2002), metabolit sekunder bukanlah produk sampingan yang “tidak
berguna”, melainkan hasil dari proses evolusi yang kompleks, di mana
tumbuhan mengembangkan mekanisme kimiawi untuk mempertahankan
diri dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Di Indonesia, pemanfaatan
metabolit sekunder banyak ditemukan dalam praktik pengobatan tradisional
berbasis tanaman, yang kemudian dikembangkan menjadi fitofarmaka
modern (Sari & Rahayu, 2020).
187