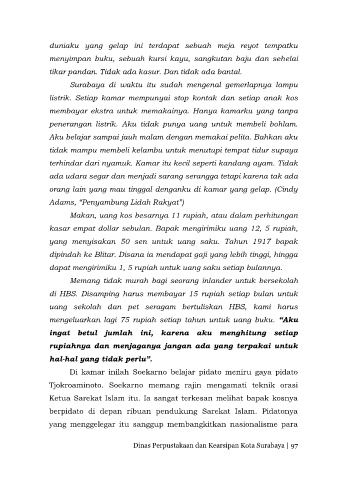Page 99 - TOKOH-TOKOH NASIONAL
P. 99
duniaku yang gelap ini terdapat sebuah meja reyot tempatku
menyimpan buku, sebuah kursi kayu, sangkutan baju dan sehelai
tikar pandan. Tidak ada kasur. Dan tidak ada bantal.
Surabaya di waktu itu sudah mengenal gemerlapnya lampu
listrik. Setiap kamar mempunyai stop kontak dan setiap anak kos
membayar ekstra untuk memakainya. Hanya kamarku yang tanpa
penerangan listrik. Aku tidak punya uang untuk membeli bohlam.
Aku belajar sampai jauh malam dengan memakai pelita. Bahkan aku
tidak mampu membeli kelambu untuk menutupi tempat tidur supaya
terhindar dari nyamuk. Kamar itu kecil seperti kandang ayam. Tidak
ada udara segar dan menjadi sarang serangga tetapi karena tak ada
orang lain yang mau tinggal denganku di kamar yang gelap. (Cindy
Adams, “Penyambung Lidah Rakyat”)
Makan, uang kos besarnya 11 rupiah, atau dalam perhitungan
kasar empat dollar sebulan. Bapak mengirimiku uang 12, 5 rupiah,
yang menyisakan 50 sen untuk uang saku. Tahun 1917 bapak
dipindah ke Blitar. Disana ia mendapat gaji yang lebih tinggi, hingga
dapat mengirimiku 1, 5 rupiah untuk uang saku setiap bulannya.
Memang tidak murah bagi seorang inlander untuk bersekolah
di HBS. Disamping harus membayar 15 rupiah setiap bulan untuk
uang sekolah dan pet seragam bertuliskan HBS, kami harus
mengeluarkan lagi 75 rupiah setiap tahun untuk uang buku. “Aku
ingat betul jumlah ini, karena aku menghitung setiap
rupiahnya dan menjaganya jangan ada yang terpakai untuk
hal-hal yang tidak perlu”.
Di kamar inilah Soekarno belajar pidato meniru gaya pidato
Tjokroaminoto. Soekarno memang rajin mengamati teknik orasi
Ketua Sarekat Islam itu. Ia sangat terkesan melihat bapak kosnya
berpidato di depan ribuan pendukung Sarekat Islam. Pidatonya
yang menggelegar itu sanggup membangkitkan nasionalisme para
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya | 97