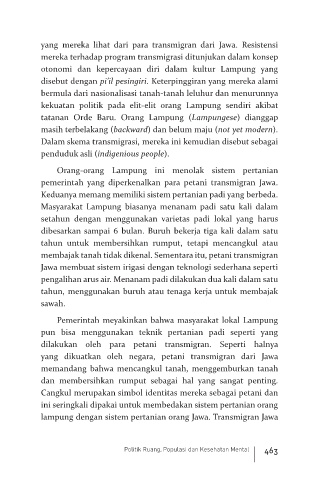Page 476 - Mozaik Rupa Agraria
P. 476
yang mereka lihat dari para transmigran dari Jawa. Resistensi
mereka terhadap program transmigrasi ditunjukan dalam konsep
otonomi dan kepercayaan diri dalam kultur Lampung yang
disebut dengan pi’il pesingiri. Keterpinggiran yang mereka alami
bermula dari nasionalisasi tanah-tanah leluhur dan menurunnya
kekuatan politik pada elit-elit orang Lampung sendiri akibat
tatanan Orde Baru. Orang Lampung (Lampungese) dianggap
masih terbelakang (backward) dan belum maju (not yet modern).
Dalam skema transmigrasi, mereka ini kemudian disebut sebagai
penduduk asli (indigenious people).
Orang-orang Lampung ini menolak sistem pertanian
pemerintah yang diperkenalkan para petani transmigran Jawa.
Keduanya memang memiliki sistem pertanian padi yang berbeda.
Masyarakat Lampung biasanya menanam padi satu kali dalam
setahun dengan menggunakan varietas padi lokal yang harus
dibesarkan sampai 6 bulan. Buruh bekerja tiga kali dalam satu
tahun untuk membersihkan rumput, tetapi mencangkul atau
membajak tanah tidak dikenal. Sementara itu, petani transmigran
Jawa membuat sistem irigasi dengan teknologi sederhana seperti
pengalihan arus air. Menanam padi dilakukan dua kali dalam satu
tahun, menggunakan buruh atau tenaga kerja untuk membajak
sawah.
Pemerintah meyakinkan bahwa masyarakat lokal Lampung
pun bisa menggunakan teknik pertanian padi seperti yang
dilakukan oleh para petani transmigran. Seperti halnya
yang dikuatkan oleh negara, petani transmigran dari Jawa
memandang bahwa mencangkul tanah, menggemburkan tanah
dan membersihkan rumput sebagai hal yang sangat penting.
Cangkul merupakan simbol identitas mereka sebagai petani dan
ini seringkali dipakai untuk membedakan sistem pertanian orang
lampung dengan sistem pertanian orang Jawa. Transmigran Jawa
Politik Ruang, Populasi dan Kesehatan Mental 463