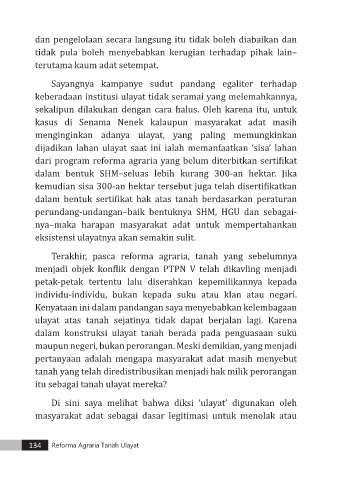Page 169 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 169
dan pengelolaan secara langsung itu tidak boleh diabaikan dan
tidak pula boleh menyebabkan kerugian terhadap pihak lain–
terutama kaum adat setempat.
Sayangnya kampanye sudut pandang egaliter terhadap
keberadaan institusi ulayat tidak seramai yang melemahkannya,
sekalipun dilakukan dengan cara halus. Oleh karena itu, untuk
kasus di Senama Nenek kalaupun masyarakat adat masih
menginginkan adanya ulayat, yang paling memungkinkan
dijadikan lahan ulayat saat ini ialah memanfaatkan ‘sisa’ lahan
dari program reforma agraria yang belum diterbitkan sertifikat
dalam bentuk SHM–seluas lebih kurang 300-an hektar. Jika
kemudian sisa 300-an hektar tersebut juga telah disertifikatkan
dalam bentuk sertifikat hak atas tanah berdasarkan peraturan
perundang-undangan–baik bentuknya SHM, HGU dan sebagai-
nya–maka harapan masyarakat adat untuk mempertahankan
eksistensi ulayatnya akan semakin sulit.
Terakhir, pasca reforma agraria, tanah yang sebelumnya
menjadi objek konflik dengan PTPN V telah dikavling menjadi
petak-petak tertentu lalu diserahkan kepemilikannya kepada
individu-individu, bukan kepada suku atau klan atau negari.
Kenyataan ini dalam pandangan saya menyebabkan kelembagaan
ulayat atas tanah sejatinya tidak dapat berjalan lagi. Karena
dalam konstruksi ulayat tanah berada pada penguasaan suku
maupun negeri, bukan perorangan. Meski demikian, yang menjadi
pertanyaan adalah mengapa masyarakat adat masih menyebut
tanah yang telah diredistribusikan menjadi hak milik perorangan
itu sebagai tanah ulayat mereka?
Di sini saya melihat bahwa diksi ‘ulayat’ digunakan oleh
masyarakat adat sebagai dasar legitimasi untuk menolak atau
134 Reforma Agraria Tanah Ulayat