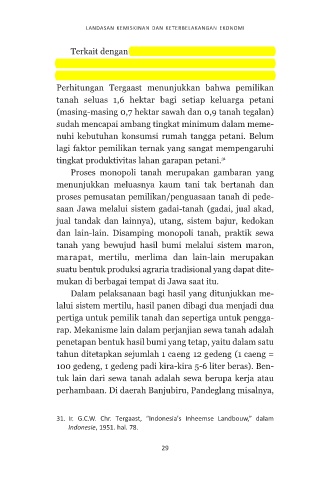Page 35 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 35
LANDASAN KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI
Terkait dengan semakin meningkatnya jumlah petani
tak bertanah di pedesaan Jawa, standar hidup yang bisa
dihasilkan dari tanah garapannya pun terus menurun.
Perhitungan Tergaast menunjukkan bahwa pemilikan
tanah seluas 1,6 hektar bagi setiap keluarga petani
(masing-masing 0,7 hektar sawah dan 0,9 tanah tegalan)
sudah mencapai ambang tingkat minimum dalam meme-
nuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Belum
lagi faktor pemilikan ternak yang sangat mempengaruhi
tingkat produktivitas lahan garapan petani. 31
Proses monopoli tanah merupakan gambaran yang
menunjukkan meluasnya kaum tani tak bertanah dan
proses pemusatan pemilikan/penguasaan tanah di pede-
saan Jawa melalui sistem gadai-tanah (gadai, jual akad,
jual tandak dan lainnya), utang, sistem bajur, kedokan
dan lain-lain. Disamping monopoli tanah, praktik sewa
tanah yang bewujud hasil bumi melalui sistem maron,
marapat, mertilu, merlima dan lain-lain merupakan
suatu bentuk produksi agraria tradisional yang dapat dite-
mukan di berbagai tempat di Jawa saat itu.
Dalam pelaksanaan bagi hasil yang ditunjukkan me-
lalui sistem mertilu, hasil panen dibagi dua menjadi dua
pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk pengga-
rap. Mekanisme lain dalam perjanjian sewa tanah adalah
penetapan bentuk hasil bumi yang tetap, yaitu dalam satu
tahun ditetapkan sejumlah 1 caeng 12 gedeng (1 caeng =
100 gedeng, 1 gedeng padi kira-kira 5-6 liter beras). Ben-
tuk lain dari sewa tanah adalah sewa berupa kerja atau
perhambaan. Di daerah Banjubiru, Pandeglang misalnya,
31. Ir. G.C.W. Chr. Tergaast, “Indonesia's Inheemse Landbouw,” dalam
Indonesie, 1951. hal. 78.
29