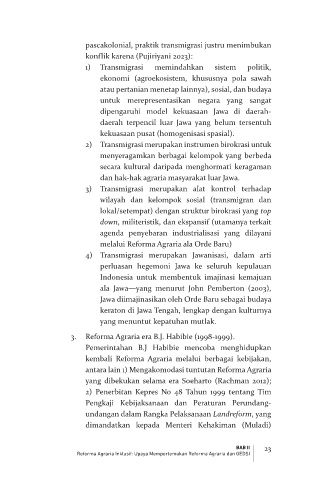Page 38 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 38
pascakolonial, praktik transmigrasi justru menimbukan
konflik karena (Pujiriyani 2023):
1) Transmigrasi memindahkan sistem politik,
ekonomi (agroekosistem, khususnya pola sawah
atau pertanian menetap lainnya), sosial, dan budaya
untuk merepresentasikan negara yang sangat
dipengaruhi model kekuasaan Jawa di daerah-
daerah terpencil luar Jawa yang belum tersentuh
kekuasaan pusat (homogenisasi spasial).
2) Transmigrasi merupakan instrumen birokrasi untuk
menyeragamkan berbagai kelompok yang berbeda
secara kultural daripada menghormati keragaman
dan hak-hak agraria masyarakat luar Jawa.
3) Transmigrasi merupakan alat kontrol terhadap
wilayah dan kelompok sosial (transmigran dan
lokal/setempat) dengan struktur birokrasi yang top
down, militeristik, dan ekspansif (utamanya terkait
agenda penyebaran industrialisasi yang dilayani
melalui Reforma Agraria ala Orde Baru)
4) Transmigrasi merupakan Jawanisasi, dalam arti
perluasan hegemoni Jawa ke seluruh kepulauan
Indonesia untuk membentuk imajinasi kemajuan
ala Jawa—yang menurut John Pemberton (2003),
Jawa diimajinasikan oleh Orde Baru sebagai budaya
keraton di Jawa Tengah, lengkap dengan kulturnya
yang menuntut kepatuhan mutlak.
3. Reforma Agraria era B.J. Habibie (1998-1999).
Pemerintahan B.J Habibie mencoba menghidupkan
kembali Reforma Agraria melalui berbagai kebijakan,
antara lain 1) Mengakomodasi tuntutan Reforma Agraria
yang dibekukan selama era Soeharto (Rachman 2012);
2) Penerbitan Kepres No 48 Tahun 1999 tentang Tim
Pengkaji Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-
undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, yang
dimandatkan kepada Menteri Kehakiman (Muladi)
BAB II 23
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI