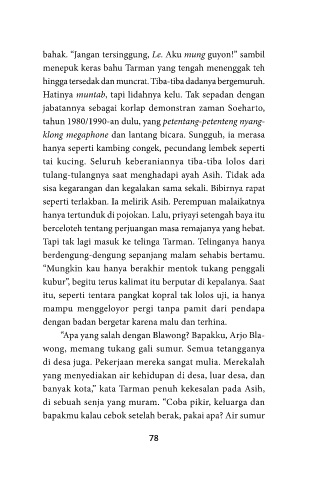Page 96 - Wabah (KUMPULAN CERPEN)
P. 96
bahak. “Jangan tersinggung, Le. Aku mung guyon!” sambil
menepuk keras bahu Tarman yang tengah menenggak teh
hingga tersedak dan muncrat. Tiba-tiba dadanya bergemuruh.
Hatinya muntab, tapi lidahnya kelu. Tak sepadan dengan
jabatannya sebagai korlap demonstran zaman Soeharto,
tahun 1980/1990-an dulu, yang petentang-petenteng nyang-
klong megaphone dan lantang bicara. Sungguh, ia merasa
hanya seperti kambing congek, pecundang lembek seperti
tai kucing. Seluruh keberaniannya tiba-tiba lolos dari
tulang-tulangnya saat menghadapi ayah Asih. Tidak ada
sisa kegarangan dan kegalakan sama sekali. Bibirnya rapat
seperti terlakban. Ia melirik Asih. Perempuan malaikatnya
hanya tertunduk di pojokan. Lalu, priyayi setengah baya itu
berceloteh tentang perjuangan masa remajanya yang hebat.
Tapi tak lagi masuk ke telinga Tarman. Telinganya hanya
berdengung-dengung sepanjang malam sehabis bertamu.
“Mungkin kau hanya berakhir mentok tukang penggali
kubur”, begitu terus kalimat itu berputar di kepalanya. Saat
itu, seperti tentara pangkat kopral tak lolos uji, ia hanya
mampu menggeloyor pergi tanpa pamit dari pendapa
dengan badan bergetar karena malu dan terhina.
“Apa yang salah dengan Blawong? Bapakku, Arjo Bla-
wong, memang tukang gali sumur. Semua tetangganya
di desa juga. Pekerjaan mereka sangat mulia. Merekalah
yang menyediakan air kehidupan di desa, luar desa, dan
banyak kota,” kata Tarman penuh kekesalan pada Asih,
di sebuah senja yang muram. “Coba pikir, keluarga dan
bapakmu kalau cebok setelah berak, pakai apa? Air sumur
78